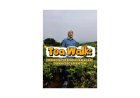Surabaya – Dunia hukum Indonesia kembali diguncang kegaduhan yang melukai nalar sehat. Kasus Hogi Minaya bukan sekadar angka dalam statistik kriminalitas, melainkan cermin retak keadilan kita.
Seorang suami yang bertaruh nyawa melindungi istrinya dari penjambret, justru harus menyandang status tersangka setelah upaya pengejarannya berujung maut bagi sang kriminal.
|
Baca juga:
Prof. Mia Amiati: Alemlaq Oasis di Mekkah
|
Ini adalah ironi besar yang menunjukkan betapa kakunya birokrasi hukum kita, yang seringkali lebih memuja teks undang-undang daripada ruh keadilan itu sendiri.
Penetapan Hogi sebagai tersangka didasarkan pada Pasal 310 dan 311 UU LLAJ tentang kelalaian yang menyebabkan kecelakaan fatal. Secara tekstual, penyidik mungkin merasa benar. Namun, hukum tanpa konteks adalah buta.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI pada Rabu, 28 Januari 2026, kemarahan para legislator meledak. Kapolresta dan Kajari Sleman "dirujak" habis-habisan karena dianggap hanya berpikir normatif.
Anggota Dewan melihat ada kegagalan fungsi diskresi di sini. Mengapa penyidik seolah-olah menganggap pengejaran jambret tersebut sebagai kecelakaan lalu lintas biasa, tanpa melihat pemicu utamanya (kejahatan penjambretan)?
Jika kita membedah lebih dalam, ada tiga pilar utama mengapa penetapan tersangka Hogi adalah sebuah kesalahan fatal secara sosiologis dan yuridis.
Pertama adalah absennya niat jahat (Mens Rea). Dalam hukum pidana, niat (intent) adalah segalanya. Hogi Minaya tidak keluar rumah dengan rencana membunuh orang. Ia merespons sebuah serangan mendadak terhadap istrinya. Tindakan memepet pelaku adalah upaya paksa yang sah secara moral untuk menghentikan pelarian kriminal. Mengabaikan aspek ini berarti menyamakan seorang pahlawan dengan seorang pembunuh jalanan.
|
Baca juga:
Prof. Mia Amiati: Mengenal Pohon Pule
|
Kedua adalah pesan buruk bagi publik. Lahirnya masyarakat apatis hukum memiliki fungsi edukasi. Jika kasus Hogi berakhir di penjara, pesan yang sampai ke masyarakat adalah "Jangan menolong, jangan melawan kejahatan, atau Anda akan dipidana." Kita sedang menciptakan bangsa yang apatis, yang lebih memilih merekam kejahatan dengan ponsel daripada memberikan bantuan karena takut akan bayang-bayang status tersangka.
Ketiga adalah pengabaian alasan pemaaf dan pembenar. KUHP kita sebenarnya sudah menyediakan "pintu keluar" yang elegan melalui konsep Overmacht (daya paksa) atau Noodweer (pembelaan terpaksa). Mengapa penyidik tidak menggunakan pintu ini sejak awal?. Mengapa harus menunggu tekanan publik dan "semprotan" dari Senayan baru kemudian melirik opsi Restorative Justice (RJ)?.
Puncak Kemarahan di Senayan
Pemanggilan Kombes Edy Setyanto ke Senayan bukan sekadar seremonial. Pernyataan keras dari Safaruddin, anggota Komisi III yang juga mantan petinggi Polri, yang menyebut ingin mencopot Kapolresta jika ia masih memiliki kewenangan, adalah sinyal bahwa institusi Polri sedang mengalami krisis persepsi hukum.
Polisi dan Jaksa seharusnya tidak hanya menjadi "juru ketik" pasal-pasal. Mereka adalah benteng terakhir keadilan. Ketika masyarakat melihat penjambret tewas sebagai risiko dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri, namun polisi justru membela hak hidup sang kriminal di atas hak pembelaan diri korban, maka di sanalah wibawa hukum runtuh.
Untungnya, desakan publik yang masif membawa titik terang. Rencana penghentian kasus melalui mekanisme Restorative Justice adalah langkah mundur yang perlu dilakukan untuk melangkah maju menuju keadilan yang hakiki. Namun, RJ seharusnya bukan menjadi "obat darurat" saat ditekan atasan atau DPR, melainkan sudah menjadi pola pikir sejak laporan pertama dibuat.
Hukum harus memiliki hati
keadilan tidak boleh dikalahkan oleh prosedur administrasi. Kasus Hogi Minaya harus menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran Polres dan Kejaksaan di Indonesia.
Hukum harus digunakan untuk membelenggu penjahat, bukan membelenggu mereka yang berani melawan kejahatan. Kita butuh penegak hukum yang peka, yang mengerti bahwa di atas hukum tertulis, ada hukum tertinggi bernama Salus Populi Suprema Lex Esto kesejahteraan rakyat (dan rasa keadilan) adalah hukum tertinggi.@Dedik.
Penulis:
Dedik Sugianto
Pemred Media Sindikat Post

 Salsa
Salsa